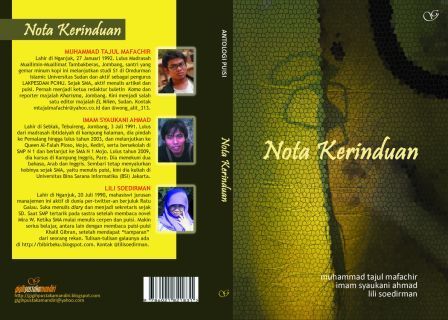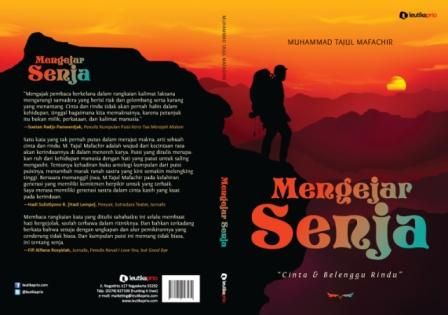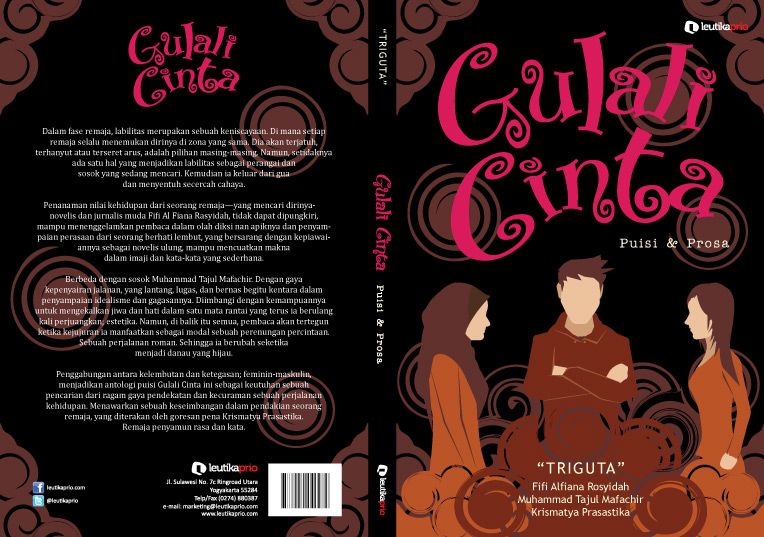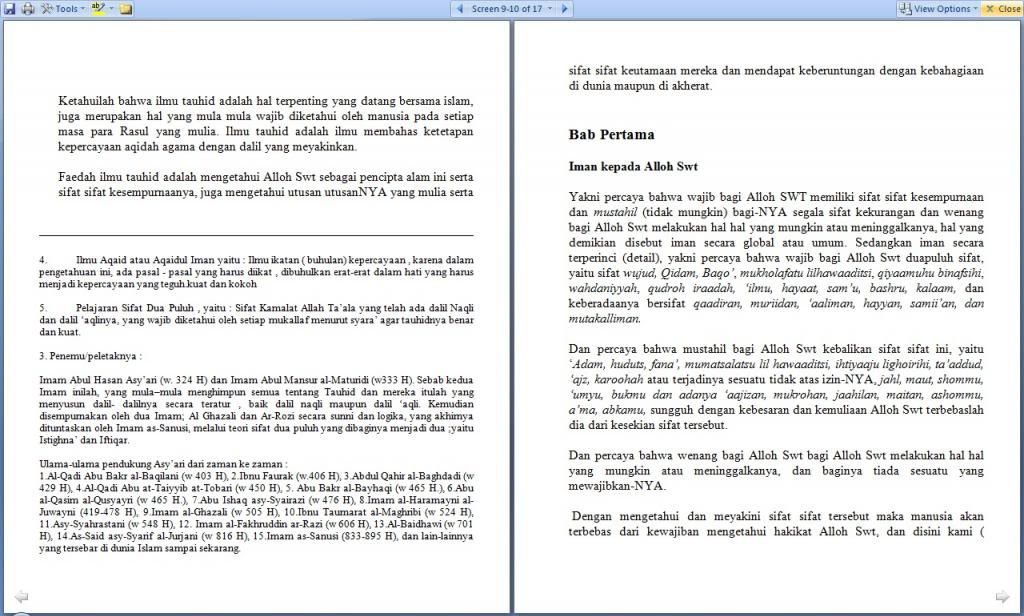Pada hari / tanggal keberapa yang
penulis lupa –jelasnya awal penulis menginjakkan kaki di Sudan (28 oktober
2011)— perkiraan selang beberapa minggu setelah kedatangan penulis bersama dua
sejawatnya: M. Satar Amrullah dan Awaliya Safithri. Sewaktu itu, tampuk
kepemimpinan Pengurus Cabang Istimewa Nahdatul ‘Ulama (PCINU Sudan) dinahkodai
oleh DR. H. Sohib Rifa’I, MA sebagai Rais Syuriah dan H. Lian Fuad, BS sebagai
Ketua Tanfidzhiyah, dengan kantor kesektretariatan berada di Arkaweet blok 48.
Sebuah rumah sederhana dengan total luas kurang lebih 40 X 25 M2. .
Terdiri dari satu ruang diperuntukan untuk kantor kerja, satu auditorium
sederhana diperuntukan untuk sentral kegiatan berdekatan dengan perpustakaan sederhana
di sampingnya –rak berisikan diktat, kitab dan literature--, kemudian satu
kamar mandi, satu ruang dapur sederhana yang dipadu dengan baseman berisikan
meja dan kursi – kursi tua tempat biasa teman – teman aktivis PCINU Sudan berdiskusi
dan berkumpul bersebelahan antara ruang dapur dan satu petak halaman kecil
berukuran 4 x 10 M2 yang merupakan tempat pilihan favorit untuk tidur malam saat
musim panas tiba.
Sore hari itu, setelah sholat
maghrib berjama’ah, Doktor Sohib menyeru para ‘penghuni’ rumah yang sejatinya
kesekretarian PCINU itu untuk berkumpul di Auditorium. Dalam hati kecil
penulis, sebenarnya sudah menyangka – nyangka beberapa hal yang mungkin,
mengenai kebijakan yang sakit didengar. Doktor Sohib meluruskan beberapa hal,
terkait beberapa permasalahan rumah yang sejatinya bertetangga langsung dengan
tuan rumah. Diantaranya, kebisingan yang sering terjadi dan jumlah penghuni
rumah yang sejatinya kesekretarian itu yang meledak. Bahkan, ketika ternyata kami
saling berhitung, pada saat itu, jumlah kami lebih dari 15. Sedangkan, teken
kontrak sewa rumah dengan tuan rumah hanya tertera tidak lebih dari 8 orang. Itu
adalah permasalahan klasik mengenai kebudayaan sewa menyewa di Sudan, katanya,
mayoritas menyewa rumah hanya boleh dihuni oleh minimal 8 orang.
Dalam hal ini, adalah konsekwensi
kita harus menghargai dan bersikap realistis terhadap kelangsungan bertetangga
sebagai kaum pendatang. konkrit faktanya, kita tidak sedang menyewa rumah untuk
kepentigan 8 orang itu, namun lebih. Karena diantara tujuan teman aktivis PCINU
menyewa rumah saat itu, adalah difungsikan sebagai kantor kesekretarian dan
sentral kegiatan para anggota NU di Sudan. Hal diatas belum diperparah drama tuan rumah
yang mengancam akan menaikan harga sewa, atau enggan diperpanjang pada kontrak
berikutnya.
Alhasil, dengan tegas penulis
akui cool, Doktor Sohib melalui lisan H. lian Fuad, BS mengambil
tindakan ‘pemutihan’ penghuni: terkait nama – nama yang berhak secara de
jure menempati rumah yang sejatinya adalah kesekretariatan. 8 orang yang
berhak tinggal, setelah melewati pertimbangan elit syuriah dan tanfidziyah pada
saat itu. Dan siapapun sudah mengira, penulis dan keenam sejawatnya tidak
termasuk, dan harus meninggalkan rumah yang sejatinya kesekretariatan itu. Demi
merenggangkan otot saraf guam –perselisihan—tuan rumah yang harus mulai
dianggap serius.
Mau tidak mau, penulis beserta
enam sejawatnya: Abdul Aziz, A. Lukman Fahmi, Farisul Arsyad, Satar Amrullah,
Ahmad Syuhada dan Barri Alhafidz memutuskan untuk membuka lembaran dan
lingkungan baru bergegas di asrama yang disediakan kampus, Omdurman Islamic
University. Sejujurnya, diantara kami, melalui percakapan – percakapan kecil
kami di sela – sela kesibukan sebagai mahasiswa, kami masih merasa berat hati
untuk memulai segalanya dari awal. Kami seolah sudah merasa nyaman, dengan
selama ini tinggal di rumah PCINU Sudan Arkaweet blok 48 yang sejatinya
kesekretariatan itu. Disana, kami sudah terbiasa bercanda, bergaul, berdiskusi
tentang hal – hal remeh temeh bersama lintas daerah dan pengalaman latar
belakang kami di Indonesia. Hal itu, bagi kami yang masih newbie –anak bawang—baru
datang di Sudan, adalah semacam obat anti-depresan yang selama ini kami cemaskan sebelum
berangkat ke Sudan. Seperti kecemasan: apakah di sudan nanti –pada ekosistem
baru, kami akan menemukan hal yang sama, minimal dalam pergaulan sesama mahasiswa
seperti laiknya selama ini kami kenal di Indonesia? Atau, disana ada teman
orang Indonesia bisa kita percaya, atau tidak?
Sejujurnya, pertanyaan –
pertanyaan kecil nan menggelikan itu, pasti timbul bagi siapa saja, termasuk
kami, ketika hendak menginjak-kan kaki di Negara yang konon seperti yang
disiarkan melalui media – media massa Indonesia yang selalu memandang ‘usang’
tentang Sudan.
Baru sedikit mendapatkan jawaban,
atas pertanyaan – pertanyaan di atas. Dan diantara kita –newbie—baru belajar
saling akrab dan bersahabat. Juga lingkungan yang membuat kita merasa nyaman,
dengan alih – alih itu kadang penulis dengan ringan berkata: ternyata sudan
itu tidak seperti yang kita sangka – sangkakan, tidak begitu menyeramkan. Disini
konflik hanya cerita sebelum tidur, yang kita dengar dari lisan – lisan senior.
Tidak seperti yang kita baca di koran – koran digital: Label Negara rawan. Pergaulan
juga hampir persis seperti di Indonesia. bahkan Banyak mahasiswa maupun
mahasiswi Indonesia di sini. Otomatis, kita punya banyak PR untuk berkenalan
diantara satu dengan mereka dan menambah teman baru. Bahkan, dalam keseharian,
seperti saya yang jawa, rasa – rasanya masih tetap menggunakan bahasa jawa dalam
percakapan. Memang saya dimana?
Pernyataan menggelikan diatas,
selalu bikin celah tawa kecil saat penulis tergiring mengingatnya.
Sedangkan diantara penulis dan
keenam sejawatnya, yang pada saat itu sudah berada di asrama. Tidak henti –
hentinya berkeluh kesah, tentang hal – hal baru yang baru perlu kami hadapi di
asrama, Futihab Omdurman. Kami berkumpul dalam satu bilik khusus yang kita sewa
untuk tempat eskap sementara kami lari, ‘diusir’ oleh mashlahat.
Diantara kami, bahkan karena saking belum mampu penuh keluar dari zona
nyaman, berceloteh banyak hal tentang kebijakan itu. Bahkan sempat kami
sepakat, bahwa Doktor Sohib bertindak otoriter dan tidak mengindahkan kami.
Namun toh, selang beberapa lama –hitungan
minggu. Kami pun sudah terbiasa dengan kehidupan baru kami di asrama. Penulis
malah sempat merasa ‘nyaman’ berada di asrama. Dimana penulis bisa
meng-kondisi-kan segala hal, terkait diri penulis pribadi dengan semau ‘gue’
dengan penuh konsekwensi yang ditanggung sendiri. Jika suatu saat penulis
sedang giat membaca, misalnya, penulis akan memanfaatkan menit – menit escaping
di asrama bermanja – manja dengan Seno Gumiro Adjidharma, Djenar Maesa Ayu, Putu
Wijaya, Phutut EA dan banyak lagi sebagai pendamping kesepian penulis di asrama.
Penulis merasa bebas, menentukan sendiri nasibnya. Tidak terjerat oleh muatan –
muatan pasar yang cenderung bersifat persuasive dan kurang bertanggung jawab.
Di asrama, penulis sendirilah, yang mau tidak
mau, menemukan jalan motivasinya sendiri, membangun keter-sadar-an sendiri,
bukan ditentukan oleh eksponen eksternal dan motif pasar. Seperti yang
sebelumnya penulis rasakan di rumah arkaweet 48 yang sejatinya kantor
kesekretariatan itu.
Di asrama, penulis bebas
menentukan lawan bergaul. Bilik kami yang bertetangga dan berdempetan dengan penguhuni
lain yang berbeda suku, budaya dan bahasa, adalah kekayaan sendiri yang pribadi
penulis rasakan sebagai ladang multicultural luas untuk kita meraba – raba saling
berkenalan antar satu sama lain. Bukan kah, merupakan tujuan prinsip yang harus
kita sadari dari diciptakannya manusia oleh Allah SWT dengan kondisi saling
bersilang gender, berbangsa dan ber-suku itu untuk kita saling mengenal satu
sama lain? Inna ja’alnaakum Syu’uban wa Qobaaila Li Ta’arafuu.
Di asrama, awal – awalnya penulis
beranikan diri berkenalan dengan teman – teman dari Thailand yang masih satu
rumpun (kalkulatif penulis). Selain mudah dalam proses berkenalannya, karena
serumpun bahasa, adat dan kebudayaan yang hampir tidak sukar dimengerti, adalah
hal – hal yang mula penulis harus bangun sebagai penghuni asrama baru yang
musti ‘sowan’ –sungkem—senior. Dan alhamdulllah, dari perkenalan itu penulis
kembangkan menjadi keakraban – keakraban yang ber-implikasi pada hal – hal yang
kemudian boleh dikatakan bermanfaat misalnya saling sharing –tukar pendapat dan
ide, atau diskusi kecil – kecilan paruh waktu. Itulah pengalaman kali pertama
penulis, berdiskusi dengan tanpa atribut apapun selama penulis berada di Sudan.
Tidak jauh hari setelah itu,
barulah penulis mulai mengembangkan sayap perkenalan dengan mahasiswa lain –bertetangga
kamar—dari lintas Negara dan benua. Penulis berkenalan dengan awal -awalnya Musyrif
sebagai ‘pengasuh’ asrama, hingga beliau kenal betul (akrab) dengan kami:
mahasiswa Indonesia. Bahkan, pada satu waktu yang tidak sengaja, kami
berkesempatan mengundang beliau untuk Futhuur (red, Breakfast) bersama
di bilik kami, dengan menu seadanya: Indomie. Setelah itu juga, penulis
berkenalan dengan teman – teman Sudan dari berbagai daerah: Darfur, Port Sudan,
Jined, Sudan barat dan sebagainya. Ada juga diantaranya, adalah orang – orang asing
dari Pantai Gading, Nepal, dan Nigeria.
Alangkah begitu, hal tersebut
rangkaian album kenangan indah yang penulis rasakan ketika berada di asrama.
Fasilitas di asrama pun, penulis
kira memadai. Disediakan tempat tidur (bahkan lemari bagi yang di IUA), kamar
mandi bersama, masjid, lapangan sepakbola atau basket, dan satu hal: dekat
dengan kampus hari – hari kita belajar. Bikin kita betah belajar dan merenung,
mengembangkan bahasa arab atau meluangkan waktu yang melimpah untuk sekedar
membaca diktat materi kuliah untuk mempersiapkan ujian yang konon menegangkan ---namun yang terakhir ini, belum berlaku bagi
pribadi penulis.
Pada hari dan tanggal keberapa
yang penulis lupa. Sedang terjadi kerusuhan di asrama, Futihab Omdurman. Yang desas
– desusnya konon kerusuhan disebabkan oleh dua hal: Pertama, kasus pembunuhan
4 mahasiswa Darfur di Jazirah –salah satu
kawasan di Sudan, oleh oknum yang disinyalir militer yang merebak kasus setelah
jenazah diketemukan di perairan sungai Nil tanpa ada kejelasan dari pihak
terkait. Kontan, hal tersebut mengundang aksi brutal dari sejumlah aktivis
mahasiswa Darfur yang menuntut penegakan hukum: dengan aksi perusakan 4 gedung
raksasa asrama Futihan. Kedua, konon ini terkait kenaikan harga tariff
tinggal di asrama. Tidak tanggung – tanggung, tariff kenaikan – nya hampir
seratus persen dari 125 SDG ke 250 SDG per-tahunnya. Hal ini lah, sebab alasan
kenapa banyak kabar menilai kenapa huru – hara terjadi. Adalah aksi protes atas
kenaikan harga tariff tinggal asrama yang dianggap tidak pro dengan kantong
mahasiswa. Malam itu para aktivis menggelar serangkaian aksi protes dengan
membakar ludes hampir seluruh asrama seisinya. Pada malam hari itu, penulis dan
keenam sejawatnya sedang tidak berada di asrama: merayakan libur tahunan di
Khartoum. Baru ke-esokan harinya penulis mendengar kabar lisan dari Ahmad
Syuhada’ lalu dibenarkan oleh para saksi kejadian –teman Thailand.
Kalau, toh, pada saat itu penulis
tidak sedang berada di Khartoum. Mungkin penulis hari ini masih memiliki asrama
sebagai sarana escaping, merenung, belajar keluar dari zona nyaman, berkenalan
dengan hal baru, menghadapi persoalan komunal, mengembangkan diri, dan pengayaan
bahasa.
Hari ini, dua tahun kurang setelah aksi brutal
itu, penulis baru sadar tentang penting dan kerugian penulis yang sudah tidak lagi memiliki asrama. Di samping
rasa sedih yang sempat penulis rasakan, juga bahkan ke-enam sejawat penulis
yang kehilangan harta benda paska kerusuhan. Detik ini Penulis berkata: Saya
menyesal, kenapa tidak tinggal saja di asrama saja.
Tak ayal, bagi penulis hanya bisa
meratapi bagaimana sikap 2 tahun yang lalu, utamanya terhadap fatwa ‘pemutihan’
Doktor Haji Sohib melalui lisan Haji Lian Fuad yang menyadarkan penulis sampai
hari ini tentang satu pasal hukum: sejatinya rumah yang dengan pembiayaan
kantong PCINU Sudan itu adalah kantor kesekretariatan dan sentral kegiatan. Tidak
lain, bukan?
Khartoum, 25 Juni 2014